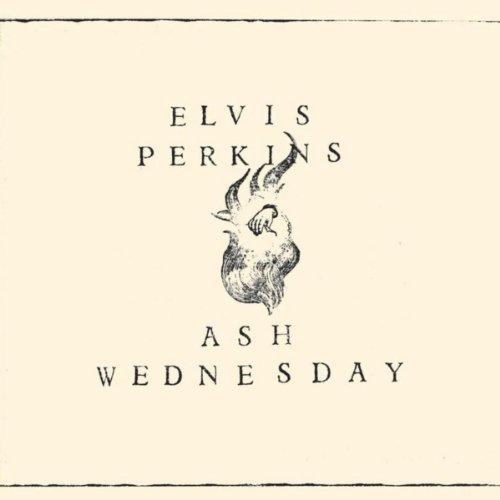It’s A Sad World After All.
Kesedihan itu hal umum di Jakarta.
Kalau sedang berada di jalan pada malam hari, tengoklah ke kanan kiri. Ada banyak kesedihan yang bisa kamu temukan. Di Jakarta. Penjual gorengan yang dagangannya tak laku. Bapak tua penjual cuanki yang berjalan dengan tertatih. Anak-anak kecil berwajah kantuk yang berdiri di lampu merah sembari memegang berbungkus-bungkus tisu untuk dijual.
Beberapa hari lalu saya membeli makan. Ayam bakar. Hujan kemudian turun. Deras. Saya melihat seorang pegawai mulai memasukkan dagangan ke tas kresek. Ada ayam, sate usus, sate rempelo ati, sate ceker, tempe, tahu. Sudah mau tutup mas, tanya saya. Dia mengangguk sembari tersenyum kecut.
Sudah jualan mulai pagi. Kalau hujan gini, apalagi tengah malam, sudah gak bakal ada yang beli. Dia bilang itu sembari terus memasukkan dagangannya yang tak laku. Seorang kawannya tetap membakar ayam yang saya pesan.
Saya menengok jam di pergelangan tangan. Sudah menjelang 12 malam.
Di perjalanan pulang, saya menyaksikan seorang bapak yang berdiri di perempatan ujung jalan Ampera Raya, di seberang Cilandak. Dugaan saya dia mau ke terminal Kampung Rambutan, untuk kemudian entah ke mana lagi. Saya sekilas menengok wajahnya. Lelah.
Seringkali saya, mungkin juga kamu dan semua orang di dunia ini, merasa sedih karena melihat orang sedih. Membayangkan betapa berat hidup sialan ini.
Saat awal hidup di Jakarta, saya berusaha benar bertahan melihat segala rupa kepiluan. Lama kelamaan mungkin saya terbiasa. Saya jadi ketakutan sendiri. Takut bahwa nanti saya bisa jadi kebal. Kemudian kehilangan rasa empati.
Saya tak mau itu.
Agar tak terlampau sering menjumpai raut-raut wajah kusut, saya menghindari pulang pada jam normal. Pada jam itu, kamu akan melihat wajah-wajah yang terdiri dari berbagai rupa: capek, lelah, marah, kesal, kosong, gemas. Segala macam rupa ada di jalan. Saya tak mau melihat wajah-wajah seperti itu. Belum lagi kalau kamu ke stasiun kereta dan menyaksikan ribuan orang menuju rumah masing-masing.
Tapi ternyata meski saya pulang semalam apapun, bahkan dini hari sekalipun, wajah-wajah seperti itu masih bisa saya temui. Lama-lama, saya tak berusaha terlalu keras untuk menghindarinya. Wajah-wajah itu seakan bilang: the more you ignore me, the closer I get.
Mereka, para manusia berwajah sedih itu, kemudian melatih saya untuk tetap tegar. Melatih agar tidak melulu mengeluh atau berkeluh kesah. Mengajarkan untuk selalu bersyukur. Klise memang. Tapi manjur, setidaknya untuk diri sendiri.
Saya tak mau jadi seperti banyak kawan yang hobi menggerutu di status media sosial. Merutuk, mengutuk, menyumpah, seperti tak ada lagi sisa kebahagiaan dalam dirinya. Seperti tak ada lagi energi tersisa untuk berkisah tentang hal kecil yang membuatnya merasa senang. Hanya bersisa marah dan marah dan marah. Seakan-akan hanya dia seorang yang punya hak eksklusif atas kekecewaan, kesedihan, juga kemarahan.
Padahal, siapa di dunia ini yang tak pernah kecewa dan sedih, atau marah?
Kalau kacamata kita perbesar, sepertinya kita tinggal di negara yang bersinonim dengan kesedihan. Juga kemarahan. Ditambah kekecewaan. Buku dibakar. Diskusi dibubarkan. Anak sekolah diperkosa ramai-ramai kemudian dibunuh. Tanah leluhur dirampas atas nama pembangunan. Bapak menghamili anak kandungnya. Anak memutilasi ibu yang melahirkannya. Yang mayoritas menghantam yang lebih sedikit. Negara brengsek ini seperti terbakar pelan-pelan, dan banyak dari kita tak bisa berbuat apa-apa selain mengutuk dan bersedih. Negara bajingan ini menjelma menjadi tempat yang sudah tak punya lagi kisah-kisah bajik, seperti yang dulu didongengkan oleh Nenek pada cucunya.
Coba tengok lagi dunia dengan suryakanta. Lebih kacau lagi. Orang beda keyakinan dibunuh. Bocah kecil tewas tenggelam. Penonton konser diberondong tembakan. Rumah sakit dibom. Saking terlalu banyak tragedi, susah untuk mengingatnya satu-satu. Mereka kemudian akan kita ingat satu dua minggu, untuk kemudian tergantikan oleh tragedi yang lain.
Tadi malam saya pulang agak cepat. Sekira jam 9 sudah sampai kontrakan. Di pagar, saya melihat sebuah gembok tergantung. Heran. Biasanya tak ada gembok. Kemudian Mas Arif, tetangga dari kamar nomor dua menghampiri. Menyerahkan satu kunci gembok.
“Hari Sabtu kemarin motor Mas Jay hilang,” katanya.
Saya nggumun. Hari Sabtu itu saya menonton Java Jazz. Baru sampai rumah sekitar pukul 2 dini hari. Kata Mas Arif, motor hilang diperkirakan pukul 3-4 pagi. Saat itu sedang hujan. Semua penghuni kontrakan sedang terlelap.
Kemudian saya membayangkan wajah Mas Jay. Pasti dia sedih. Kehilangan. Bisa jadi motor itu punya banyak kenangan bagi Mas Jay dan istrinya. Motor merek V berwarna putih itu tetap dia pakai ke mana-mana meski dia sudah punya mobil.
Tapi tadi malam, setelah menerima kunci gembok, saya tak sempat ketemu Mas Jay. Pintu kontrakannya tutup. Mungkin sudah istirahat. Lagi-lagi terbayang raut muka sedih Mas Jay, juga mereka yang kehilangan, apapun itu.
Saya masuk kamar. Melepas celana panjang. Menghidupkan lampu dapur. Memotong tomat kecil-kecil. Juga acar timun. Menuang mayonaise. Memberinya susu kental manis. Saya mengambil lemon dari kulkas. Menyerut sedikit kulitnya. Memotong sedikit bagian, kemudian memeras sarinya. Saya mengolesnya pada dua tangkup roti tawar. Juga membuat telur mata sapi. Saya menyantapnya sembari memutar Ash Wednesday.
I am in the mood of grey and blue tonight.
Elvis Perkins pun mengingatkan saya akan fitrah dunia ini. “It’s a sad world after all,” katanya. Murung. Kelabu. Muram. Sialan. Saya benci menjadi sedih. Tapi apa boleh buat. It’s a sad world after all. Suka tidak suka, diakui atau tak diakui, kesedihan memang bukan barang langka di dunia ini.
Apalagi di Jakarta. []